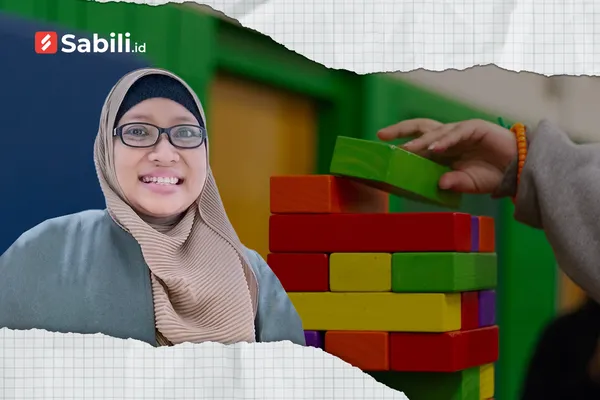Psikolog, Farida Aini, menegaskan, banyaknya kasus kenakalan anak dan remaja pasti punya korelasi dengan pola asuh orangtua di dalam rumah mereka. Menurut dia, pola asuh adalah cara sang orangtua mengasuh anaknya. Sebenarnya, selain oleh orangtua si anak sebagai “Significant Person” atau orang yang sangat berpengaruh terhadap anak, pola asuh juga bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang ada di sekitarnya. Lewat pola asuh itu pula, anak-anak harus tahu apa yang baik dan yang buruk serta apa yang boleh dan yang tidak boleh.
“Anak-anak sekarang termasuk Generasi Alfa. Generasi Alfa adalah mereka yang lahir di tahun 2000 sampai 2020. Ini generasi yang dari kecil sebenarnya sudah terpapar oleh gadget. Bagaimana cara mendidik mereka? Orangtua ada kalanya bisa menerapkan pola dengan memainkan peran sebagai pembuat aturan yang jelas dari awal, tetapi ada kalanya dia juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan maunya seperti apa, lalu negosiasi,” katanya.
Lebih lanjut, Pemilik lembaga Farida Aini Consulting ini menjelaskan, ada empat tipe pola asuh. Tetapi dalam perkembangannya dikembangkan menjadi lima tipe pola asuh. Pertama, pola asuh “Otoriter”. Di tipe ini, orangtua cenderung menerapkan pola asuh yang sifatnya “Instruksi”. Biasanya ada aturan-aturan yang ketat, anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide atau perasaannya.
“Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter, ketika sudah remaja dan dewasa, dia cenderung menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Lalu karena biasa diberikan ‘Instruksi’, dia mudah terpengaruh oleh orang di sekitar. Dia butuh pegangan. Ketika misalnya sudah remaja, dia akan ikut ‘Peer Groups’. Teman sebaya itu penting buat dia. Karena di rumah dia sudah terbiasa dengan ada aturan yang jelas, kaku, A harus A, B harus B, maka ketika sudah remaja dan boleh jadi hubungan dengan orangtuanya tidak dekat, maka dia menganggap teman sebaya dialah sebagai pemberi instruksi. Boleh jadi, dia ikut-ikutan. Kata teman harus A, oke dia ikut. Nggak terbiasa untuk berfikir kritis,” katanya.
Kedua, pola asuh “Permisif”. Permisif adalah pola asuh yang membebaskan anak-anak. Tidak tahu aturan kaku. Efeknya, ketika sudah besar, sang anak menjadi sulit untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Sebab, semasa kecil itu ia dibesarkan dengan pola penerapan aturan yang terserah maunya. Orangtua tak mengajari etika.
“Contohnya, ketika kecil anak itu naik ke atas meja, padahal meja itu bukan tempat untuk duduk, tetapi orangtua membiarkan dan tidak pernah memberitahu agar tidak duduk di atas meja. Sehingga dia tak tahu bahwa itu salah. Ketika remaja, boleh jadi ia menganggap tawuran sebagai sesuatu yang boleh dilakukan. Bisa jadi dia juga ikutan kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya,” katanya.
Ketiga, pola asuh “Neglect”. Artinya pengabaian. Ketika orangtuanya cuek, tidak merespon anaknya, hal itu juga memberikan pengaruh. Misalnya, anaknya mengatakan, “Ibu, saya dapat prestasi,” tetapi ibunya tidak merespon, maka ketika remaja ia jadi tak tahu mana hal yang positif dan negatif, serta dia harus merespon apa.
“Sebenarnya yang paling bagus adalah pola asuh “Demokratis”. Boleh jadi, anak-anak demokratis dari kecil itu sudah diajari bahwa dia boleh mengungkapkan pendapatnya, dia boleh mengeluarkan idenya, sehingga sejak kecil dia terbiasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Orangtua tetap mengontrol, tetapi tidak mengekang seperi otoriter,” ujarnya.
Farida melanjutkan, jika melihat tipe-tipe pola asuh tersebut, bisa diprediksi hal itu akan berpengaruh ketika ia beranjak remaja. Jika misalnya dia berkembang dengan pola asuh demokatis, ia bisa berpikir kritis. Misalnya, tawuran ini efek negatifnya apa, dan dia bisa mengatakan kepada teman-temannya tentang pendapatnya. Misalnya, ketika temannya mengajak untuk menyerang kelompok lain karena sebelumnya kelompok lain itu menyerang kelompok mereka, ia bisa berfikir, apakah hal itu baik atau tidak.
“Dia punya kesempatan itu, karena dari kecil sudah dibiasakan untuk bertanya, dibiasakan untuk mencoba ambil keputusan sendiri walaupun orangtua tetap memperhatikan. Biasanya, mereka tumbuh sebagai remaja-remaja yang kritis dan cukup tahu apa yang mereka mau. Intinya, kenakalan remaja sangat punya korelasi dengan pola asuh orangtua,” ucapnya.
Lalu bagaimana cara membentuk pola kebiasaan yang baik? Farida menyebut, yang pertama adalah membuat aturan yang jelas di dalam rumah. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, jika sudah selesai makan, anak itu diminta untuk membawa piring dan peralatan makannya yang kotor ke dapur. Atau ia dibiasakan untuk meletakkan dan menyusun sendiri sepatunya di rak sepatu. Dari aturan sederhana itu, menurut dia, bisa menjadi pola dan anak itu menjadi tahu kebiasaan baik.
“Termasuk pengunaan gadget. Kalau misalnya menggunakan gadget hanya boleh di hari Sabtu-Minggu selama dua jam, dan hal itu ditegaskan kepada dia, anak itu terbiasa oleh itu. Di dalam hal ini orangtua punya kontrol.
Penggunaan gadget itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sebua reward. Misalnya, dia senang main game. Maka ketika dia misalnya mengerjakan tugas-tugasnya dan ia berhasil setiap hari menjalankan tanggung jawab, di saat weekend dia dapat reward boleh main game.
Pola-pola seperti itu sebenarnya harus diterapkan. Terkait pengunaan gadget, orang tua harus ‘tega’ demi kebaikan anak. Masalahnya, justru kadang-kadang orangtua merasa, daripada si anak berisik dan menganggu pekerjaannya, maka anaknya diberikan handphone. Diasumsikan, kalau anaknya diam karena asik main hp dan tidak menganggu, itu bagus.
Padahal efeknya dalam jangka panjang itu sangat buruk. Sebaiknya, buatlah aturan, lalu berikan aktivitas lain misalnya mainan puzzle, ego, diberi buku-buku bacaan, diajak main di luar, didorong bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, dan sebagainya. Jadi dia tidak terfokus pada permainan yang ada di gadget. Cara-cara itu akan membentuk perilakunya,” urainya.
Kadang orangtua menafsirkan perilaku memanjakan anak sebagai curahan kasih sayang. Akhirnya, anak itu punya kendali terhadap orangtuanya. Padahal, menurut Farida, ungkapan kasih sayang tidak harus seperti itu. Tetapi, anak-anak diberi pemahaman, karena mereka harus tahu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan seterusnya.
Orangtua bisa memilah hal-hal yang baik untuk anaknya. Jika berefek negatif buat anak, orangtua harus tegas melarang. Jadi, pemberian kasih sayang bukan dengan memanjakan, tetapi bagaimana menunjukkan bahwa lewat kasih sayang itu orangtua bisa mengajari anak dengan tegas tentang hal yang baik dan buruk. Tanpa memarahi atau menghukum.
“Orangtua harus belajar mendodrong anak agar berpikir kritis dan demokratis. Orangtua harus tahu periode usia anak-anak, misalnya usia balita itu adalah masa ‘golden age’ buat anak. Usia emas. Di situ simulasinya harus banyak, karena di situ perkembangan tanggung jawab 80% optimal.
Orang tua harus mengambil momen itu. Sangat penting punya kedekatan dengan anak, sehingga anak merasa nyaman dengan orangtua. Jika sudah merasa nyaman, ia akan bercerita segala macam kepada orangtua, tidak ada rahasia, sehingga ketika sudah besar pun modeling atau contoh buat dia adalah orang tuanya,” katanya.
Jadi penting sekali bagi orangtua untuk memberikan kasih sayang dengan tetap membangun kemandirian anak. Aturannya dibentuk. Sehingga, dia belajar menemukan cara terbaik supaya otaknya berkembang, kemampuan motoriknya berkembang, rasa welas asih di dalam dirinya juga berkembang.
“Momennya adalah di masa balita. Itulah momen terbaik untuk membentuk moral dan seterusnya. Karena di masa itu golden age-nya. Di momen itu, membersamai anak-anak adalah sangat penting, menurut saya. Berikan mereka kesempatan bermain dengan orangtua, sehingga dia tidak asik bermain dengan gadget. Di kemudian hari, ia akan terbuka dengan orangtuanya dalam menjalin komunikasi. Itu yang sangat penting,” jelasnya.
Baca juga :



Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!