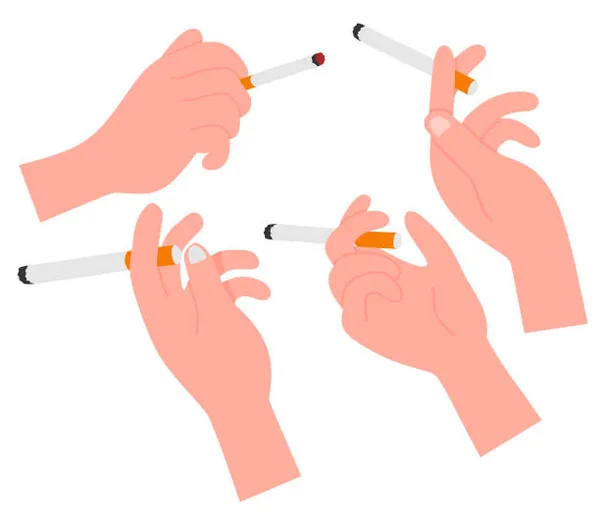Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menanggapi viralnya kasus seorang kepala sekolah yang menampar siswanya karena ketahuan merokok di sebuah SMA negeri di Banten. IDEAS menyebut, peristiwa itu bukan hanya soal kekerasan di sekolah, tetapi juga menjadi sinyal nyata bahwa bahkan lingkungan di dalam sekolah pun masih rentan atas maraknya peredaran rokok. Hal itu dikatakan Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS, Agung Pardini, dalam siaran pers yang diterima Redaksi Sabili.id, pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurut IDEAS, sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah sepatutnya menegakkan aturan yang ketat mengenai peredaran rokok dan perilaku merokok, sebagaimana yang telah dilakukan untuk kasus-kasus perundungan. Perlunya sekolah menegakkan aturan ketat tentang peredaran rokok dan perilaku merokok itu karena berdasarkan survei yang IDEAS lakukan pada 2024, terungkap betapa luas dan mengakarnya kebiasaan merokok di kalangan anak miskin desa, bahkan sejak usia sekolah dasar.
Survei IDEAS ketika itu melibatkan responden sejumlah 106 perokok anak dan remaja dari rumah tangga miskin di 54 desa tertinggal dan sangat tertinggal di 13 kabupaten pada lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta.
"Hasilnya sangat mengejutkan, yaitu 69,8 persen responden perokok anak tersebut adalah perokok aktif; 18,9 persen merokok sesekali; dan 11,3 persen baru mulai belajar merokok," kata Agung Pardini.
Agung menambahkan, sebagian besar responden yaitu 58,5 persen mulai merokok di usia SMP (13–15 tahun); 25,5 persen sudah mencoba sejak SD (6–12 tahun); dan 15,1 persen baru mulai merokok di usia SMA (16–19 tahun).
“Fase mengenal rokok dan fase menjadi perokok aktif hampir tidak memiliki jarak waktu. Begitu anak mencoba, mereka langsung terjerat menjadi perokok aktif,” ungkap Agung.

Sebanyak 46,2 persen anak dan remaja mengaku mulai mengalami kecanduan rokok saat SMA. Kata Agung, kebiasaan itu berimplikasi langsung terhadap pola konsumsi dan masa depan pendidikan mereka.
Survei IDEAS tersebut juga menemukan bahwa 36,7 persen uang saku anak miskin dihabiskan untuk membeli rokok. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makanan dan minuman (32,6 persen), transportasi atau BBM (20,2 persen), dan pulsa atau kuota internet (10,5 persen).
“Rokok kini seolah menjadi kebutuhan pokok baru dalam rumah tangga miskin. Akibatnya, alokasi untuk nutrisi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya berkurang,” tutur Agung.
Dari sisi pendidikan, sebanyak 14,2 persen perokok anak hanya tamat SD, 50 persen berhenti di SMP, dan hanya 35,8 persen yang menamatkan SMA. Temuan ini memerlihatkan bahwa perilaku merokok berhubungan erat dengan tingginya angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin.
IDEAS juga mencatat, sejumlah 67,9 persen perokok anak dan remaja mendapatkan rokok dari orang lain — terutama teman dan tetangga. Sebanyak 5,7 persen yang mendapatkannya dari keluarga inti, dan hanya 2,8 persen dari keluarga non-inti semisal paman atau kakek.
"Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial di luar rumah, termasuk sekolah, jauh lebih dominan dalam membentuk perilaku merokok anak,” jelas Agung.

Kebiasaan saling berbagi rokok di kalangan teman sebaya juga memerkuat fase kecanduan. Sehingga, Agung menilai, semestinya sekolah diberikan peran lebih besar dalam mengendalikan ekosistem merokok di lingkungannya.
“Sekolah harus menjadi ruang yang benar-benar bebas rokok, tidak hanya dari konsumsi, tetapi juga dari promosi dan penjualan,” tegasnya.
IDEAS juga menegaskan, permasalahan merokok di kalangan keluarga miskin bukan sekadar isu kesehatan, tetapi masalah kebijakan publik yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Di sisi lain, IDEAS juga menyoroti gencarnya iklan dan promosi rokok yang menyasar kelompok muda. Menurut Agung, iklan-iklan itu menancapkan asosiasi positif bahwa merokok identik dengan nilai kebebasan, maskulinitas, dan petualangan.
“Di tengah banjir iklan, kesadaran publik soal bahaya rokok tenggelam. Anak-anak miskin yang tumbuh dalam kondisi terbatas justru menjadi target paling empuk,” ujarnya.
Maka, IDEAS mendorong pemerintah memerketat larangan iklan, promosi, dan penjualan rokok di sekitar sekolah. Terutama di wilayah perdesaan yang rentan.
“Minimal dalam radius beberapa ratus meter dari sekolah, tidak boleh ada toko yang menjual rokok atau menampilkan iklan rokok,” tegas Agung.
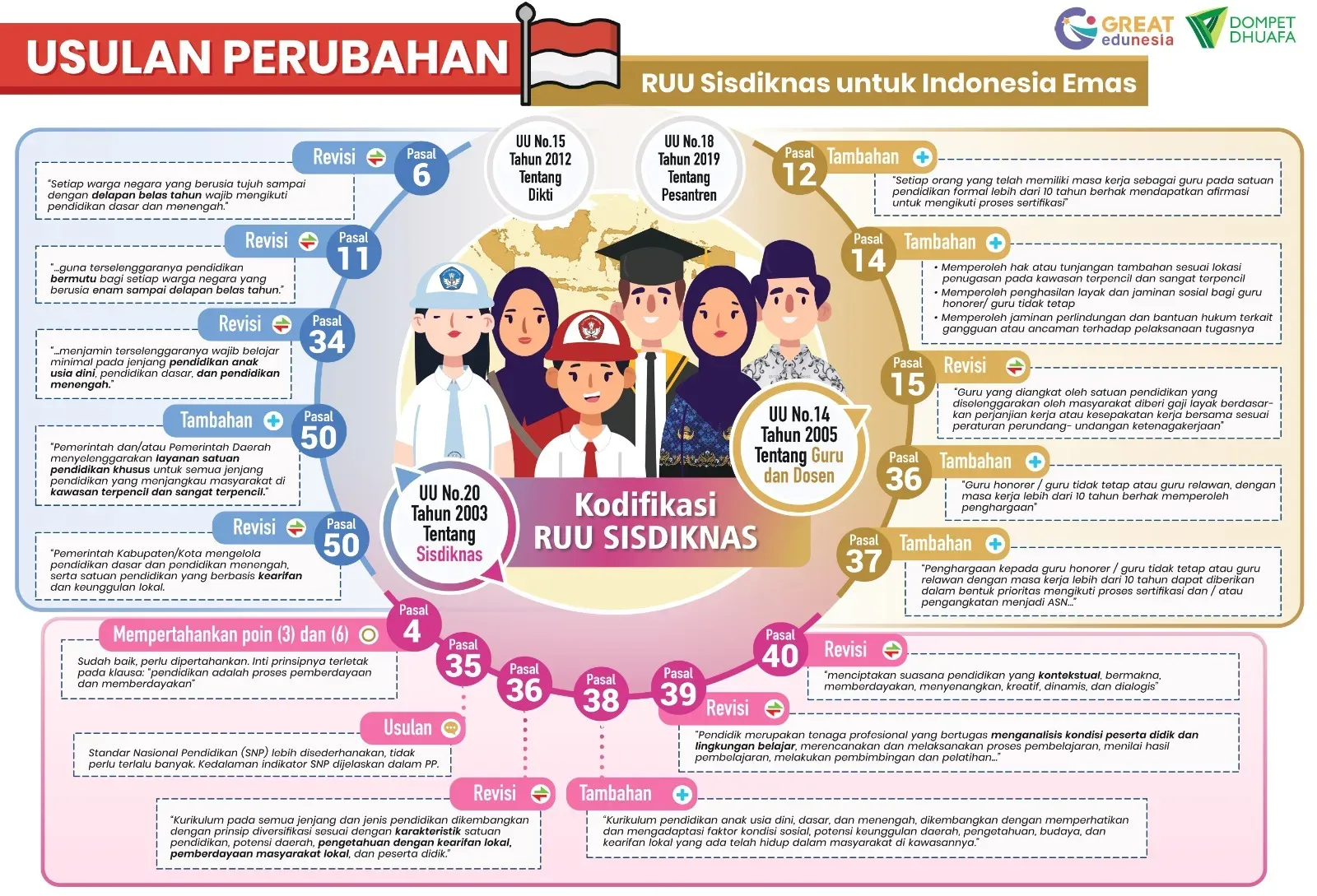
Dari serangkaian riset tersebut, IDEAS menyimpulkan bahwa faktor-faktor di luar rumah, baik dari lingkungan sosial maupun sekolah, terbukti lebih banyak memengaruhi anak untuk mulai merokok hingga akhirnya menjadi perokok aktif. Kebiasaan saling berbagi rokok di antara teman sebaya membuat fase kecanduan semakin dalam.
“Di sinilah semestinya sekolah diberikan peran aktif dalam mengendalikan pembentukan ekosistem merokok di kalangan siswanya,” kata Agung.
Selain faktor lingkungan eksternal, kata Agung, iklan rokok juga berperan besar dalam meningkatkan prevalensi perokok pemula, khususnya di kalangan anak dan remaja.
"Kesadaran publik yang sebenarnya sudah terbangun tentang bahaya rokok terus tenggelam karena dihantam bertubi-tubi oleh beragam strategi iklan dan gencarnya promosi,” tutur Agung.
Agung menegaskan, perlu keberanian politik untuk melawan dominasi industri rokok yang kerap berdalih di balik penyelamatan nasib ribuan pekerja dan jaringan hulu hingga ke hilirnya. Tanpa keberanian politik itu, berbagai upaya edukatif hanya akan menjadi slogan moral semata.
“Setiap batang rokok yang dibakar anak miskin berarti sebagian uang makan, uang sekolah, bahkan masa depan yang ikut terbakar,” tutupnya.

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!