Wajah pendidikan kita selalu diwarnai hal-hal mengejutkan di seputar polemik guru dan siswa. Hal ini kian sering terjadi dalam 10 tahun terakhir. Polemik guru dan siswa di Indonesia mencerminkan krisis nilai dan komunikasi di dalam sistem pendidikan. Tragedi demi tragedi menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan semata soal transfer ilmu, tetapi juga soal membentuk manusia. Butuh keberanian, empati, dan kerja bersama agar kisah tragis itu tidak terus berulang.
Kisah tragis di seputar polemik antara guru dan siswa di Indonesia mencerminkan ketegangan yang terjadi dalam dunia pendidikan, di mana nilai-nilai moral, budaya, hukum, dan dinamika sosial saling bertabrakan. Kasus-kasus yang terjadi begitu membuat miris. Banyak guru menjadi korban akibat konflik yang terjadi.
Ada guru yang dipenjara karena menegur siswa (kasus 2016 - Buton, Sultra); siswa menganiaya guru hingga tewas (kasus 2018 - Sampang, Madura); seorang guru yang matanya cacat karena diketapel oleh orang tua siswa (kasus 2023 - Rejang Lebong, Bengkulu); dan lain-lain. Yang terakhir dan sedang viral adalah kasus dinonaktifkannya seorang Kepala Sekolah di SMAN 1 Cimarga, Banten, karena menegur siswa yang kedapatan merokok.
Kasus terakhir ini cukup banyak menyedot perhatian netizen. Bisa jadi karena masyarakat mulai sadar bahwa banyaknya kasus para guru yang "dihukum" karena menegur dan mendisiplinkan siswa sudah harus jadi perhatian penting dan mendapat jalan keluar yang adil. Jangan sampai guru, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dalam realitanya benar-benar tak dianggap berjasa. Pendidikan yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, beralih menjadi pendidikan yang menginjak marwah para pencetak generasi itu.
Penulis juga sangat merasa miris melihat sikap pemerintah, dalam hal ini Gubernur Banten, ketika menanggapi kasus di SMAN 1 Cimarga tersebut. Seharusnya tidak perlu terburu-buru memberi sanksi kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Yang harus dilakukan adalah tabayyun dan memertemukan kedua pihak yang bertikai, baru cari solusi terbaik. Banyaknya siswa berdemonstrasi dan mogok sekolah tak perlu membuat panik pemerintah. Yang banyak itu bukan berarti yang benar. Pemerintah harus menjadi teladan terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sebijak dan seadil-adilnya yang bisa diupayakan. Walau pada akhirnya, setelah banyak tuntutan dari netizen, kepala sekolah diaktifkan kembali jabatannya.
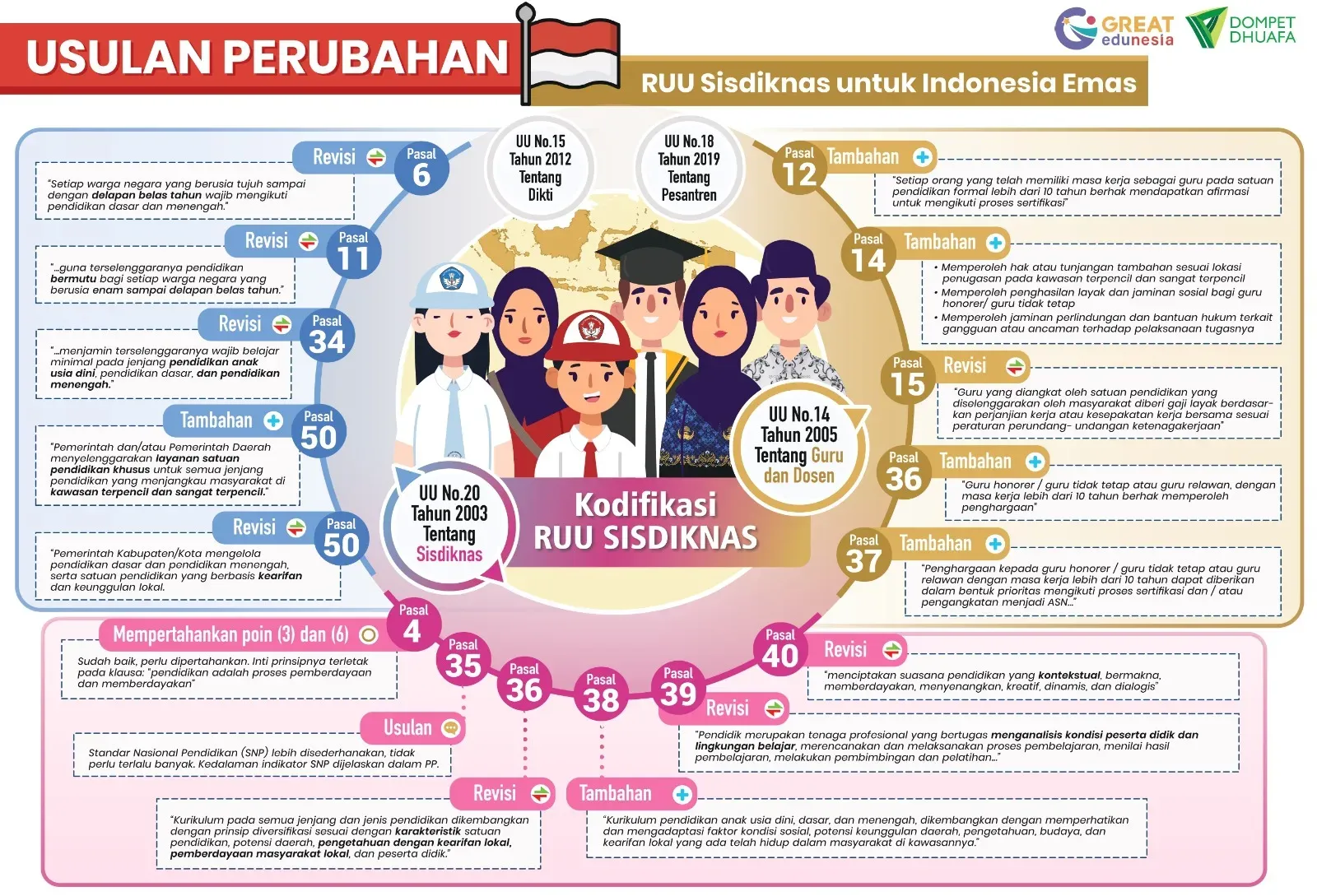
Generasi X yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 dan Generasi Y yang lahir antara 1981 hingga 1996, tumbuh dalam suasana pendidikan yang keras tetapi menjadi generasi cepat sadar diri. Mengapa disebut sadar diri? Gen X dan Y memiliki resiliensi tinggi karena mereka hidup di masa transisi besar secara sosial, ekonomi, dan teknologi. Tekanan dan tantangan yang mereka alami justru menjadi "sekolah kehidupan" yang membentuk ketangguhan mereka dalam menghadapi kesulitan. Jangankan hanya ditegur guru, dicubit dan dijewer pun kala itu sudah biasa.
Kondisinya berbeda dengan generasi masa kini yang cepat mengeluh dan mudah patah. Gaya hidup dan pola disiplin disinyalir menjadi faktor yang membuat perbedaan ini. Di era digital ini, manusia dialiri informasi yang tak terbendung dan sangat cepat, juga fasilitas yang melimpah, sehingga kehidupan menjadi lebih mudah.
Gaya parenting orang tua juga mengalami pergeseran. Overproteksi (perlindungan yang berlebihan, red) sejak anak-anak kecil sudah sering kita lihat dalam keseharian mereka. Banyak Gen Z yang tumbuh dalam lingkungan yang cenderung melindungi mereka dari kegagalan atau kesulitan. Sehingga, mereka kurang punya pengalaman menghadapi tantangan berat secara langsung. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial juga sering menciptakan standar hidup yang tidak realistis, membuat tekanan sosial lebih besar, dan bisa mengakibatkan mereka merasa mudah patah jika dibandingkan dengan orang lain. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat dan kurangnya pembelajaran soal manajemen emosi dan coping skill pun menyebabkan kegagalan mengelola stres dan tekanan.
Di dalam hal literasi, kita juga melihat ada peran yang tak bisa diremehkan dalam membangun karakter, akal budi, dan moral. Tentu saja, literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis. Tetapi literasi lebih tentang memahami pesan dan hikmah yang disampaikan secara menyeluruh. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk berpikir secara mendalam, membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat, dan tidak mudah percaya pada informasi yang salah atau menyesatkan.
Literasi adalah kemampuan dasar yang amat penting yang hari-hari belakangan ini semakin tak mendapatkan ruang. Jangankan anak, orang tua pun kurang melek literasi. Dunia digital yang seharusnya memermudah, akhirnya justru menjadi bumerang. Kasus SMAN 1 Cimarga, Banten, menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak gegabah bertindak. Apalagi jika persoalan tersebut terkait anak kita yang melanggar peraturan sekolah.
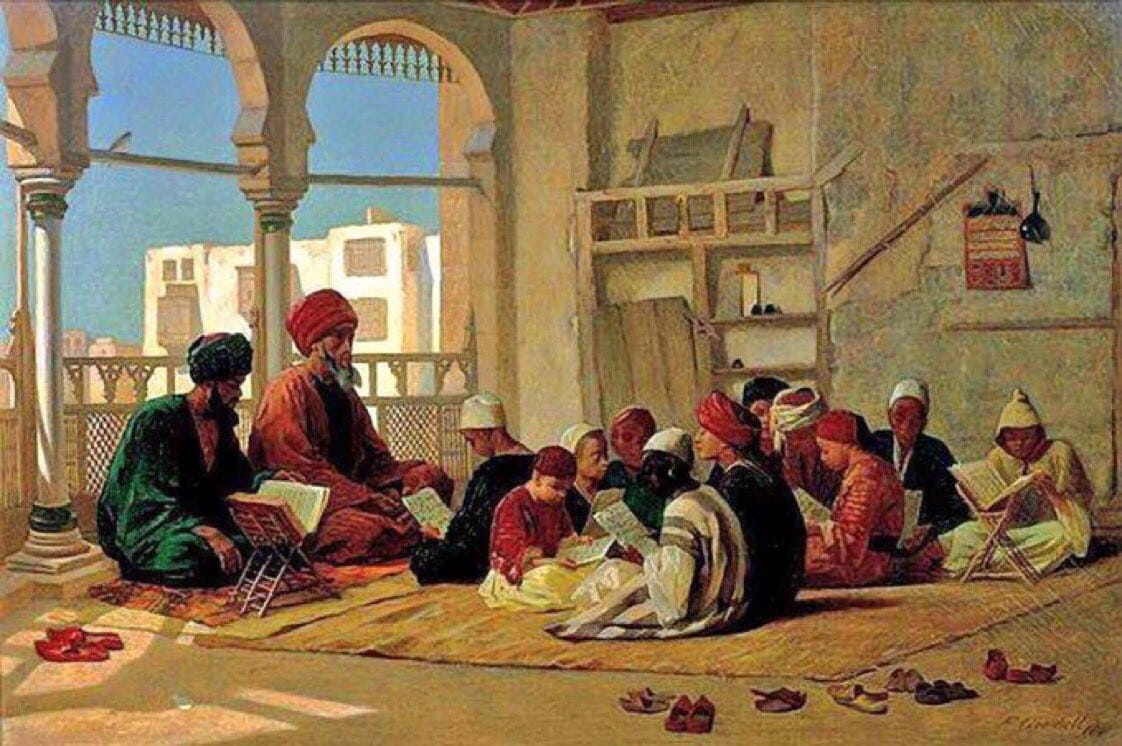
Jika saja kisah-kisah bermakna dan dongeng penuh hikmah banyak melingkupi keseharian anak-anak kita, penulis yakin jiwa mereka akan terasah dan lebih peka dalam merespons apa saja hal-hal yang ada di sekitarnya dan memiliki perspektif yang luas untuk memutuskan sesuatu. Tidak menjadi generasi yang sangat mudah memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan matang. Yang didahulukan hanya kepentingan dirinya sendiri yang amat sempit dan sementara.
Jika kita mengingat pesan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, kita akan kembali pada tiga variabel pendidikan yang masih terus relevan untuk terus dikuatkan fungsinya, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Ketiganya adalah pilar pendidikan yang terhubung satu sama lainnya. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Ketiganya harus saling bersinergi agar pendidikan berhasil mencetak manusia yang berkarakter, cerdas, dan bermoral.
Pendidikan di Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua berperan sebagai pendidik utama dalam membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan dasar anak. Nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian banyak terbentuk dari keluarga. Sedangkan pendidikan di Sekolah adalah tempat pendidikan formal berlangsung. Guru berperan sebagai pendidik profesional yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Sekolah juga menjadi tempat interaksi sosial awal di luar keluarga yang harus mampu bersinergi dengan orang tua dalam menguatkan nilai-nilai baik yang sudah ada di rumah. Jangan sampai kedua variabel penting ini timpang satu sama lain.
Pendidikan di masyarakat pun tak kalah penting. Pendidikan non-formal dan informal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ada di sini. Masyarakat memberi pengaruh lewat norma, budaya, adat istiadat, dan lingkungan sosial. Hal ini sangat berperan dalam memerluas pengalaman dan membentuk kesadaran sosial serta tanggung jawab sebagai warga negara.
Kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan diharapkan mampu menguatkan karakter baik pada anak-anak. Misalnya kegiatan gotong-royong, olah raga, kajian Islam, silaturahmi warga, lomba, dan lain-lain. Warga satu terhadap warga lainnya bisa menjadi extended family yang memberikan impact satu sama lainnya dan saling menjaga. Jangan sampai kehadiran anak-anak kita di masyarakat malah mendapatkan pengaruh yang justru buruk dari hari ke hari, semisal narkoba, LGBT, miras, hamil di luar nikah, dan lain-lain.
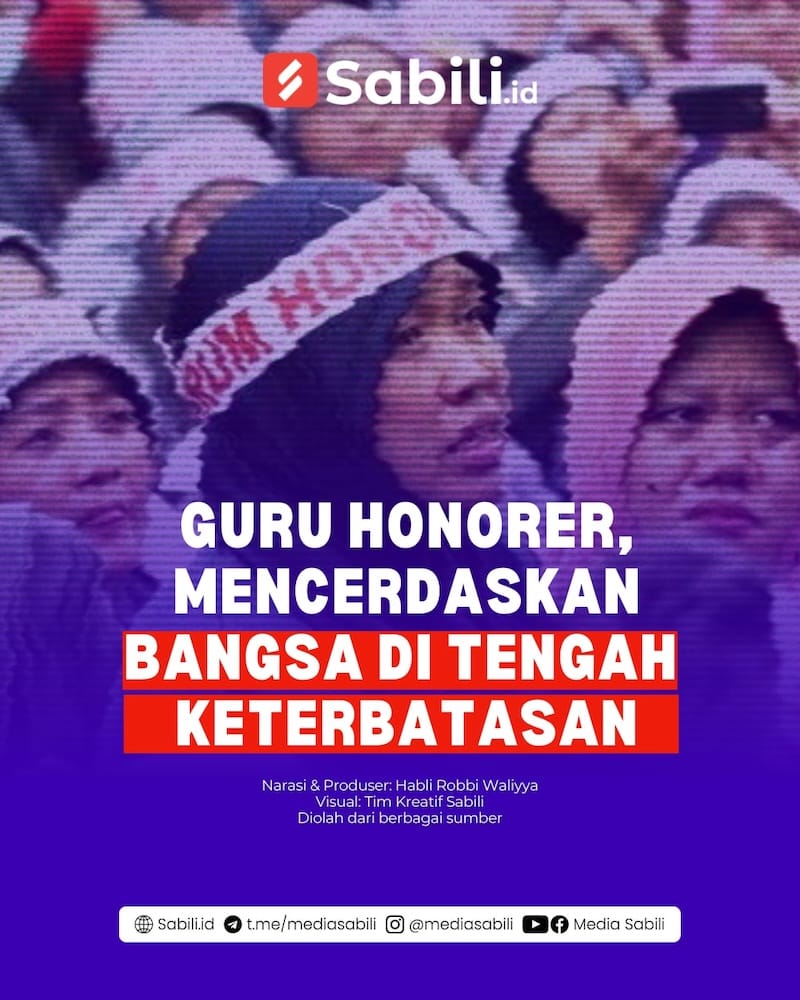
Literasi memegang kunci penting yang akan membuat ketiga variabel di atas berjalan baik. Manusia yang matang literasi, akan matang pikiran dan jiwanya, sehingga masalah apa pun dipandang sebagai sesuatu yang bisa dicarikan solusinya. Manusia yang matang literasinya juga akan selalu bersemangat untuk memberikan pengaruh baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakatnya.
Pada akhirnya, kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus memulai diri dari peningkatan literasi, baik proses pendidikan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu kutipan paling terkenal terkait hal itu datang dari Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”.
Kutipan itu menggarisbawahi bahwa pendidikan - dan membaca, sebagai bagian fundamental dari pendidikan - adalah kunci untuk menciptakan perubahan besar. Program literasi bukan sekadar lipstik penghias juga seremonial semata. Tetapi benar-benar merupakan sesuatu yang disadari sepenuhnya dapat mengubah peradaban secara mendasar dan tepat.

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!



























