Belum satu tahun, peristiwa yang mengguncang jagat hukum dan pendidikan di Indonesia. Anak SD di Tasikmalaya meninggal dunia karena depresi. Penyebab depresinya membikin banyak pihak terhenyak. Bocah malang tersebut adalah korban bullying dari teman-teman sebayanya. Ia dipaksa menyetubuhi seekor kucing dan perbuatan itu direkam. Rekamannya bahkan sempat beredar di media sosial.
Kenakalan yang aneh dan benar-benar tidak lumrah dilakukan oleh anak SD. Dari mana ide itu mereka dapatkan?
Ada peristiwa lain yang tak kalah sensasional. Di Ponorogo, ratusan siswi yang terdiri dari anak jenjang pendidikan SMP dan SMA mengajukan cuti hamil di sekolahnya. Mayoritas karena hamil di luar nikah. Yang mengajukan dispensasi nikah jumlahnya mencapai 191 anak. Pemerintah setempat mengabulkan dispensasi untuk 176 di antaranya.
Lain lagi di Makassar. Di awal tahun 2023, dua remaja berusia 17 tahun dan 14 tahun membuat kehebohan yang lain. Mereka bersekongkol untuk membunuh anak berusia 11 tahun karena tergiur jual-beli organ tubuh manusia. Bayangkan, anak-anak seusia itu menculik dan kemudian membunuh untuk memperjual belikan organ tubuh korbannya melalui internet!
Berita dramatis yang lain muncul dari kota Gorontalo. Bulan Maret lalu, Sekda kota Gorontalo dalam suatu workshop menyebut ada 10.000 pecandu Narkoba di Kota Gorontalo. Di dalam paparannya, teridentifikasi bahwa 40% dari total angka tersebut ternyata masih berusia anak-anak. Artinya, ada 4.000 anak yang telah menjadi konsumen Narkoba di Kota Gorontalo.
Rilis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 20 Maret 2023 menyebut, sepanjang tahun 2020 hingga 2022, tercatat ada 2.304 kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak. Kejahatan pencurian menduduki rangking teratas dengan jumlah kasus mencapai 838. Narkoba 341 kasus, penganiayaan 232 kasus, senjata tajam 153 kasus, pelecehan seksual 173 kasus, pembunuhan 48 kasus, pemerkosaan 26 kasus, dan seterusnya.
Kisah dan data yang mestinya mengganggu kenyamanan hidup kita. Bagi pihak yang peduli, tentu hal itu menerbitkan beragam pertanyaan. Bagaimana itu semua bisa terjadi?
Teknologi Informasi Jadi Kambing Hitam
Ada pertanyaan yang umum dan sering kita dengar. Orang tua dan pendidik yang gelisah juga kerap menanyakan hal serupa. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Pertanyaan itu memang mudah untuk dilontarkan, namun jawabannya tak pernah mudah didapatkan. Ada banyak faktor yang berkelindan dan saling menunjang, sehingga lahir persoalan-persoalan seperti yang dialami oleh para remaja tersebut.
Bahkan bisa jadi, berbagai potret persoalan yang kita ungkap di atas sesungguhnya hanyalah simptom dari persoalan sosial yang lebih besar dan mendasar. Inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya pertanyaan, “Bagaimana itu semua bisa terjadi?” Pertanyaan yang tak pernah mudah dijawab.
Namun dalam pandangan masyarakat dan orang tua di rumah, setiap masalah yang muncul mestilah ada pihak yang harus bertanggungjawab dan dipersalahkan. Sebab, upaya pencegahan dan pengendalian baru akan dijalankan jika biang kerok telah ditemukan. Sehingga, wajib ada pihak yang disalahkan.
Menyalahkan pemerintah, tentu saja tidak berani. Pastinya belum tentu juga pemerintah yang salah. Menyalahkan guru, tidak ada data yang mendukung bahwa guru patut disalahkan. Menyalahkan para ulama, apalagi. Tidak ada jejak kesalahan para ulama di sana. Jika sembrono menyalahkan para pihak tanpa data, bisa-bisa berurusan dengan hukum karena tuduhan fitnah dan ujaran kebencian.
Pada akhirnya, para orangtua, pendidik, dan bahkan mungkin pemerintah, kompak menyalahkan pihak yang tidak bisa membantah, marah, dan merasa difitnah atas tuduhan tersebut. Pihak itu adalah teknologi informasi dengan segala perwujudannya: Gadget, TV digital, HP, tablet, dan seterusnya.
Tak bisa dimungkiri, dengan teknologi informasi dalam genggaman, anak-anak di era digital memang lebih mudah memperoleh informasi serta memiliki jangkauan pergaulan yang luas hingga menembus batas teritori suatu negara. Mereka boleh jadi lahir dan tinggal di kampung, namun mampu berselancar hingga lintas negara, budaya, dan nilai.
Tentu itu semua berpengaruh terhadap pandangan, nilai, maupun perilaku anak-anak di era digital. Akses informasi yang bahkan tak lagi bisa dibatasi oleh umur, kepantasan, tabu, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan oleh masyarakatnya, sudah barang tentu turut menggoreskan kesan dan pengaruh. Nah, kesan dan pengaruh inilah yang lambat laun mengubah sudut pandang, cara berpikir, dan pada akhirnya mengubah perilaku.
Intensitas hubungan anak-anak dengan teknologi informasi dan produk turunannya begitu tinggi. Banyak yang lebih akrab dengan teman main di dunia maya, daripada dengan anak tetangga sendiri. Saat pegang gadget, panggilan ibu kandung pun bisa tak terdengar.
Kesimpulannya, terlalu banyak fakta yang bisa digunakan untuk menyalahkan teknologi informasi sebagai biang kerok munculnya masalah. Semua pihak juga setuju. Teknologi informasi juga tak bisa menyangkalnya, karena memang ia tak bisa menyangkal!
Masalahnya, mengapa anak-anak itu menjadi begitu akrab dengan internet? Bukankah kita sebagai orangtua adalah pihak yang paling berkuasa untuk menentukan kapan sebaiknya anak-anak dikenalkan dengan gadget, internet, dan sejenisnya? Bukankah YouTube dan game online dapat berada dalam jangkauan anak-anak, karena diam-diam sesungguhnya kita ingin membagi tugas dan amanah pengasuhan anak dengan gadget?
Terkait pengasuhan. Anak menangis, kita hibur dengan YouTube. Anak marah, kita hibur dengan game online. Lalu kita menyalahkan perangkat cerdas itu, saat pola asuh yang salah itu melahirkan banyak persoalan.
Jadi, menjawab pertanyaan “Bagaimana itu bisa terjadi?”, tampaknya perlu kita selami batin kita masing-masing. Terutama terkait dengan amanah pengasuhan yang harus kita – para orangtua – pertanggung jawabkan di hadapan Allah azza wajalla. Jadi, jangan buru-buru mengambinghitamkan teknologi. Sebab, jangan-jangan kesalahan pola asuh-lah yang menjadi masalah dasar kita.
Baca juga :

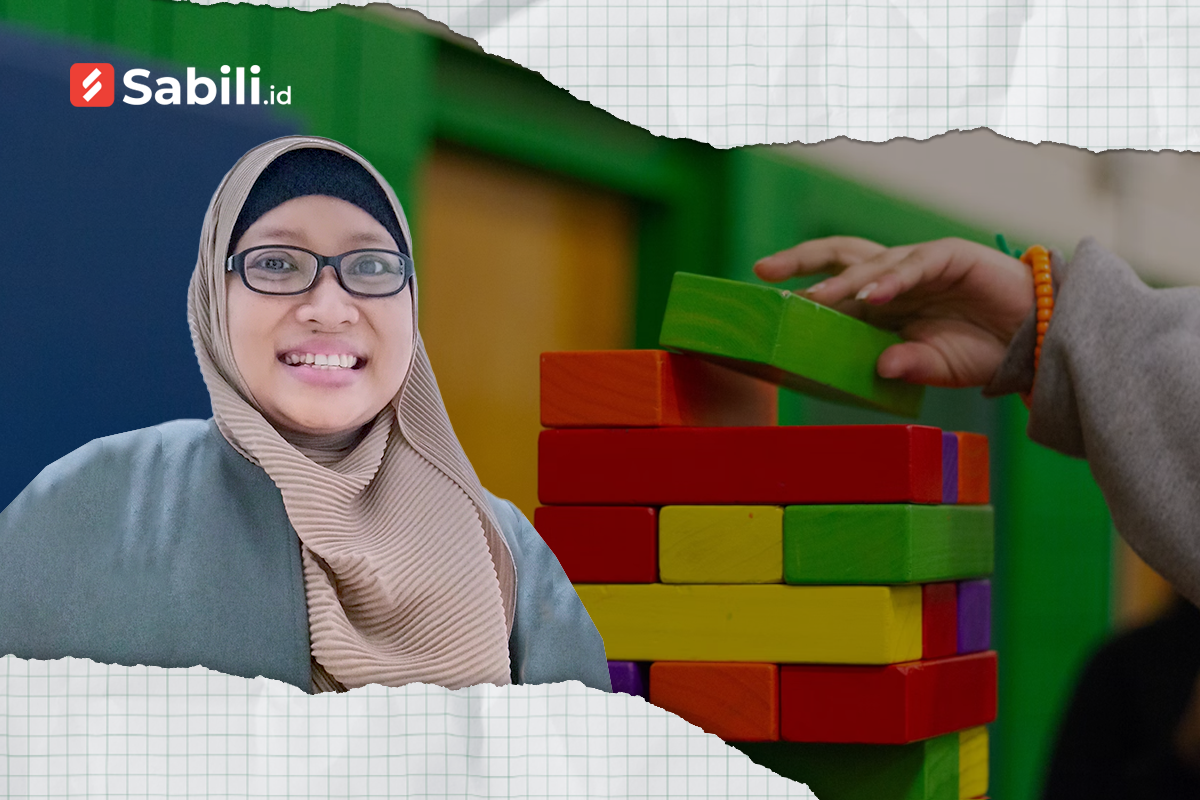

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!

























