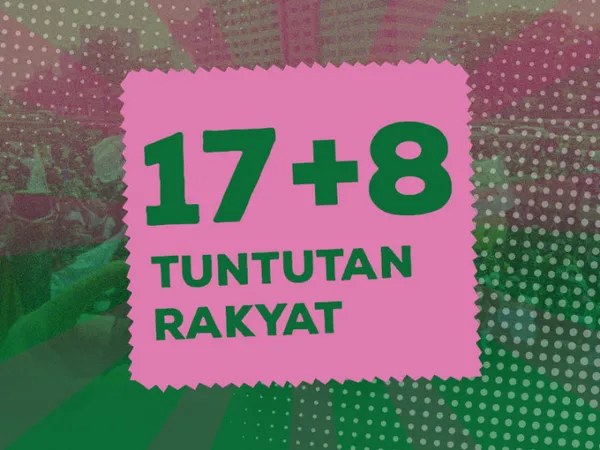Gelombang protes yang meledak Agustus lalu melahirkan sebuah simbol baru yang cepat mengakar, bernama “17+8”. Simbol ini menjadi rangkuman keresahan rakyat yang sudah terlalu lama diabaikan. Tujuh belas tuntutan jangka pendek dipadukan dengan delapan tuntutan jangka panjang.
Angka “17+8” itu menyatukan amarah rakyat pada angka 17 yang merujuk pada hari kemerdekaan (17 Agustus) dengan bulan 8 (Agustus) yang merupakan bulan perlawanan itu sendiri. Rakyat menuntut merdeka dari keserakahan elite, merdeka dari ketidakadilan, dan merdeka dari sistem yang kian jauh dari semangat republik.
Isi dari “17+8” itu pun gamblang. Pada sisi 17 tuntutan jangka pendek, rakyat mendesak agar DPR segera menghentikan kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak masuk akal, mencabut fasilitas perumahan, menutup keran kunjungan kerja ke luar negeri yang hanya menghamburkan uang, serta mengaudit seluruh anggaran yang selama ini kerap diselewengkan.
Sementara pada sisi 8 tuntutan jangka panjang, rakyat menembakkan peluru reformasi yang lebih dalam. Mereka mendesak agar sistem partai politik dibenahi, sehingga kursi kekuasaan tidak lagi hanya menjadi arena transaksi politik dan dinasti keluarga. Mereka menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, agar harta para koruptor bisa ditarik kembali untuk rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir pejabat dan kroni. Juga revisi menyeluruh atas undang-undang kepolisian dan militer, agar aparat benar-benar berada di bawah kendali rakyat, bukan alat represi. Hingga rakyat menuntut kebijakan ekonomi yang lebih berpihak, sebuah desain fiskal yang tidak lagi menindas masyarakat kecil dengan pajak yang berat sementara korporasi besar melenggang bebas.

Lantas, apakah tuntutan itu benar-benar direspons? Sejauh mana respons atas tuntutan itu? DPR memang buru-buru mengumumkan penghentian tunjangan perumahan, membekukan kenaikan gaji dan tunjangan, serta membatasi perjalanan luar negeri. Mereka juga membuka ruang transparansi anggaran dan mendorong Badan Kehormatan untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. Tetapi, pencapaian ini hanya menyentuh tiga hingga empat poin dari total “17+8”. Itu pun sebatas permukaan.
Beberapa tuntutan lain baru dimulai, meski belum jelas ujungnya: Partai politik mulai bicara soal sanksi terhadap kader yang tak etis, sejumlah serikat buruh diajak berdialog, wacana upah layak dan perlindungan pekerja kontrak masuk dalam pembahasan, TNI dan partai politik berjanji akan mengurangi intervensi di ranah sipil. Namun, semua ini baru langkah awal yang mudah pupus jika tak dikawal rakyat.
Mayoritas tuntutan justru masih terbengkalai. Reformasi partai politik belum menyentuh akar, RUU Perampasan Aset mandek di parlemen, revisi UU Kepolisian dan TNI belum berjalan, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat belum kelihatan. Lebih parah lagi, ada poin-poin yang bukan hanya tak dijawab, tetapi malah mundur: Kriminalisasi demonstran masih berlangsung, aparat pelaku kekerasan belum diadili, bahkan tindakan represif terhadap rakyat makin brutal.
Penguasa memberi sedikit konsesi di sisi fasilitas DPR, tetapi menahan reformasi fundamental yang paling ditunggu rakyat. Publik mulai curiga, semua ini hanya strategi meredam gejolak, bukan itikad membenahi negeri.

Di dalam Islam, jabatan publik adalah amanah. Harta rakyat adalah amanah. Dan pemimpin yang justru memerkaya diri dengan fasilitas berlebih telah mengkhianati amanah. Al Qur’an menegaskan, amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan diputuskan dengan adil. Begitu pula prinsip ‘adl — keadilan yang menjadi ruh syariat. Bagaimana mungkin rakyat terus dicekik biaya hidup, sementara elite sibuk memertahankan hak-hak istimewa? Tuntutan “17+8” sesungguhnya adalah seruan agar amanah dan keadilan ditegakkan kembali.
Membuntuti dinamika ini, Lukman Hakim Saifuddin, mantan menteri agama, menegaskan, "Presiden perlu memimpin respons ini. Kalau pun tidak langsung, Presiden bisa menunjuk juru bicara resmi yang menjelaskan progres. Transparansi inilah yang dinanti rakyat," jelasnya.
Di tengah sorotan publik terhadap “17+8”, sejumlah pengamat menilai bahwa ada tuntutan yang justru sangat vital namun terlupakan dalam narasi resmi simbol ini. Said Didu, pegiat anti korupsi, menegaskan, “Pernyataan ‘17+8’ perlu diteliti karena menghilangkan 3 tuntutan utama publik yang terkait dengan geng Solo, yaitu: Ganti Kapolri, makzulkan Gibran, dan adili Jokowi. Diganti dengan tuntutan yang sangat anti-TNI. Ini permainan geng Solo-oligarki-parcok?”
Komentar ini menjadi relevan karena publik kini melihat adanya pergeseran fokus. Sementara “17+8” menekankan tuntutan reformasi yang luas — dari audit anggaran hingga revisi UU kepolisian dan TNI — beberapa tuntutan konkret yang menyasar figur tertentu dari Geng Solo terkesan “hilang” dari daftar utama. Di dalam konteks ini, Said Didu menyoroti adanya tendensi untuk mengekang TNI yang justru bisa terlihat mendiskreditkan institusi militer, padahal TNI memiliki peran strategis menjaga kedaulatan negara.

Faktor internal penyusunan “17+8” juga menjadi sorotan. Seorang sumber publik mengungkap, “FYI, yang nyusun ‘17+8’ Genk Pink Ijo itu Salsa dan Polin. Awalnya Salsa nyusun 12 poin, kemudian si Polin ingin gabung juga. Lalu mereka rembugan, dan keluarlah ‘17+8’ hasil kesepakatan mereka berdua. Numpang tanya, yang ngaku Pink Ijo, tuntutan apa yang mereka tampung dari kalian?”
Pernyataan itu menunjukkan bahwa simbol “17+8” lahir dari kompromi internal kelompok tertentu. Bukan representasi utuh dari seluruh aspirasi publik.
Di sisi lain, para pengamat menekankan pentingnya keseimbangan. Memang ada risiko jika kekuasaan terlalu dipegang oleh aparat, polisi negara bisa menghadapi distorsi kekuasaan yang merugikan rakyat, namun pada saat yang sama, publik juga tidak ingin TNI memegang kontrol terlalu penuh. Oleh karena itu, pembahasan reformasi institusi keamanan harus proporsional, mengakui kebutuhan akan kontrol sipil tanpa melemahkan TNI, yang tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertahanan.
Dengan perspektif ini, “17+8” dapat dilihat sebagai panggilan moral yang lebih kompleks. Tidak hanya soal tuntutan jangka pendek dan panjang yang tercantum, tetapi juga soal bagaimana tuntutan yang “hilang” atau terpinggirkan, seperti pengawasan terhadap ‘Geng Solo’ dan figur publik, dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Rakyat menuntut keadilan, namun sekaligus harus menyeimbangkan kontrol terhadap seluruh institusi, baik legislatif, eksekutif, maupun aparat keamanan.
Rangkaian tuntutan rakyat memerlihatkan keresahan yang nyata. Sebagian mungkin sudah disentuh, sebagian lain masih dibiarkan terbengkalai. Bahkan ada yang terkesan disembunyikan, seperti desakan terkait figur-figur utama penguasa. Semua ini menegaskan, elite lebih sibuk menjaga stabilitasnya sendiri ketimbang berani menghadapi akar masalah.
Islam sejak awal telah mengingatkan, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS An-Nisa: 58).
Islam mengingatkan, amanah kepemimpinan tidak boleh dipelintir untuk kepentingan dinasti dan golongan. Namun, publik juga harus tetap jernih, tidak larut dalam arus propaganda yang menyesatkan.
Karena itu, biarlah rakyat yang menimbang apakah tuntutan ini sungguh jalan menuju perubahan, atau sekadar manuver politik yang mengulang pola lama. Waktu dan konsistensi akan membuktikan, dan publik-lah yang akan memberi penilaian terakhir, karena rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!