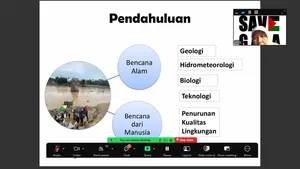Aceh memang selalu unik dan berbeda. Dengan segala keunikannya itu, Aceh memang pantas menyandang Daerah Istimewa.
Di tengah bencana yang penanganannya masih jauh dari yang semestinya, ramai diberitakan bahwa Pemda Aceh meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terlibat membantu penanganan banjir. Sontak, kabar tersebut memicu perbincangan yang riuh di berbagai media mainstream dan aneka platform media sosial. Juga menyulut pro kontra, tentang pantas atau tidaknya Pemda Aceh berkoordinasi dengan dunia internasional terkait penanganan bencana di kawasan mereka.
Mereka yang pro atas langkah yang diambil oleh Pemda Aceh berargumen; level bencana memang di luar kapasitas kemampuan penanganan Pemerintah Daerah. Bantuan dari pusat juga dianggap lamban dan serba tidak memadai! Di dalam situasi seperti itu, meminta bantuan asing demi menyelamatkan jiwa dan masa depan rakyat banyak bisa dibenarkan.
Sementara pihak yang kontra menilai langkah Pemda Aceh sebagai pelanggaran etik yang serius. Berkoordinasi dengan pihak asing adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Pemda Aceh dianggap lancang, bahkan dinilai membangkang dari kebijakan nasional yang telah menetapkan bahwa bencana Aceh bukanlah bencana nasional dan Presiden Prabowo Subianto bahkan telah terang-terangan menolak bantuang asing. Alasannya, kekuatan dalam negeri masih cukup untuk menangani bencana level provinsi itu.

Gubernur Aceh sendiri merasa tak tahu-menahu soal itu. Ia menyangka telah terjadi kesalahpahaman. Menurut dia, Aceh memang bersurat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki program di Aceh. Nah, beberapa LSM yang memiliki program di Aceh adalah lembaga-lembaga yang menjadi bagian langsung dari PBB, di antaranya adalah Unicef dan UNDP.
Politik di Balik Bencana
Banyak pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat yang enggan menetapkan bencana banjir di Aceh sebagai bencana nasional. Bahkan beberapa kalangan aktivis telah lantang menyerukan untuk menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional. Amnesty Internasional bahkan secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, agar bencana ekologis di Aceh dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional.
Fakta di lapangan memang menunjukkan skala kerusakan yang parah dan lambatnya penanganan. Lebih seribu orang tewas, banyak lagi yang masih dinyatakan hilang. Indikator keparahan yang lain adalah rusaknya infrastruktur. Listrik tidak menyala, jalanan tidak bisa digunakan, sinyal internet tidak ada, rumah–rumah penduduk hilang terbawa air. Bangunan yang tersisa juga tidak bisa dimanfaatkan karena masih tertutup lumpur yang amat tebal.
Itu semua berakibat lambannya pertolongan, bantuan, dan evakuasi korban selamat. Jelas, sumber daya yang dimiliki provinsi tak akan mampu mengurai masalah tersebut dalam waktu yang cepat. Bayangkan, jika korban selamat dari banjir masih terisolasi dari bantuan dan evakuasi dalam waktu lebih dari tiga hari tanpa air bersih, makanan, dan penghangat tubuh, korban jiwa justru bisa bertambah.

Jika pemerintah pusat menganggap mampu menangani krisis kemanusiaan ini berbasis potensi dalam negeri, tolong segera ditunjukkan. Faktanya, listrik masih padam dan masih banyak desa yang belum terjamah bantuan karena jalan darat belum bisa dilalui.
Mengapa pemerintah pusat bersikukuh tidak menaikkan status bencana di Aceh menjadi bencana nasional? Pertanyaan ini banyak berdengung di jutaan kepala rakyat Indonesia. Yang tahu persis jawabannya adalah pemerintah pusat. Banyak kalangan berspekulasi, pertimbangan politik yang lebih dipegang oleh pemerintah pusat daripada pertimbangan kemanusiaan!
Sebagaimana disebutkan di atas, Aceh memang unik dan berbeda. Konteksnya lebih kepada aspek historis dan politik. Bencana ini menjadi sangat sensitif bagi pemerintah pusat dan bahkan rakyat Aceh sendiri.
Pengalaman konflik panjang dan keterlibatan internasional pasca tsunami 2004 menjadikan setiap komunikasi ke luar negeri sarat makna politik. Bagi sebagian kalangan di pusat, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran akan “internasionalisasi” isu domestik, meski pun dibungkus dengan alasan kemanusiaan. Di titik ini, trauma sejarah bertemu dengan kecemasan administratif.
Hal lain yang patut juga kita renungkan, Uni Eropa pernah melarang, bahkan menolak minyak sawit dari Indonesia. Alasannya, Uni Eropa khawatir dengan dampak deforestasi dan ancaman terhadap lingkungan hidup akibat “kesembronoan” Indonesia dalam mengembangkan industri ini.

Tentu saja Indonesia melawan mati-matian kebijakan Uni Eropa itu. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggugatnya ke WTO. Baru Januari 2025, muncul putusan WTO yang memenangkan gugatan Indonesia atas sengketa itu. Minyak sawit Indonesia pun bebas melenggang di pasaran Uni Eropa.
Lalu bencana banjir di Sumatera terjadi. Isu deforestasi menguat kembali. Kayu-kayu gelondongan nongol bertumpuk-tumpuk seakan memunculkan diri sebagai bukti. Apakah ini yang membuat pemerintah pusat begitu hati-hati dengan munculnya bantuan asing? Bukankah Uni Eropa akan dapat bukti baru deforestasi?
Catwalk Politik Pencitraan Para Penjilat
Rakyat Aceh pantas marah dan muak. Itu pula yang mungkin dirasakan oleh para pemimpin daerahnya. Bencana Aceh ternyata tak hanya mengenaskan. Ia kini menjelma menjadi catwalk untuk memperagakan kepedulian. Masuk TV nasional? Centang. Viral di TikTok? Centang. Feed Instagram rapi, angle dramatis, caption penuh empati, pastinya centang.
Pejabat datang, tentu bukan tangan kosong: rombongan staf, fotografer, dan videografer turut dibawa. Tak lupa, rombongan pengawal. Sumbangan? Nanti dulu. Yang utama adalah dokumentasi.
Warga mungkin tak butuh pengawal, tetapi kamera jelas perlu jarak aman. Lalu, dengan penuh penghayatan, pejabat itu jongkok satu menit, meraih tangan korban banjir sambil memandang jauh ke genangan air, pose reflektif penuh empati. Klik. Momen tersimpan. Warga masih lapar? Ah, nanti dulu, post Instagram harus naik sebelum sore.

Seorang pejabat sibuk memikul karung, mungkin bukan untuk membantu rakyat tetapi untuk mengerek karir politiknya sendiri. Yang lain menjilat kepada atasannya, listrik dilaporkannya telah menyala 99%, BBM stabil, tenda sudah berdiri, dan lain-lain. Faktanya, itu semua hanya pencitraan, asal bapak senang!
Pejabat yang lamban. Tidak sadar bahwa tugas utamanya adalah membantu presiden untuk melayani rakyat. Mereka justru sibuk melayani dan menyenangkan presiden dengan tipu-tipu. Urusan bencana pun terbengkalai. Kerjaannya nol besar. Berita kekonyolannyalah yang besar-besar terpampang di media sosial rakyat.
Rakyat Aceh mengibarkan bendera putih. Pemda Aceh pun mengetuk pintu bantuan Unicef. Lalu keriuhan terjadi. Kita berharap Pemda Aceh salah secara adminitratif belaka, tak harus dibesar-besarkan. Justru yang kita khawatirkan adalah jika Pemda Aceh malah ikut mengimbangi rampak gendang politik yang ditabuh pemerintah pusat. Bak gayung bersambut, "Lu jual Gue beli". Jika begitu halnya, pastilah rakyat yang akan semakin sengsara.
Mari kita tepikan dulu urusan politik. Kiranya bencana menyatukan hati kita, untuk fokus pada penanganan masalah, penyelamatan dan perbaikan, serta kembali ke jalan yang benar.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Rum: 41).

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!