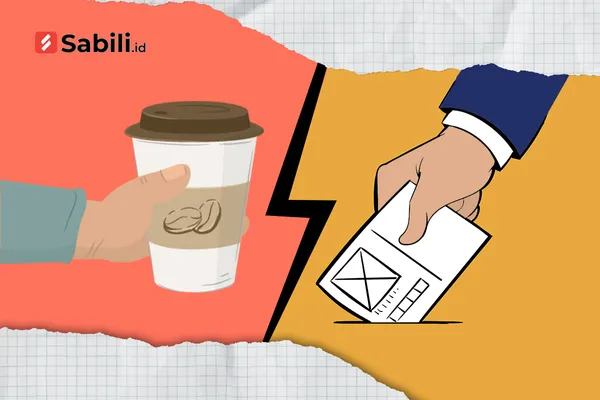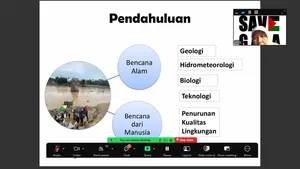Masa kecil kuhabiskan di daerah pedesaan di Sumatera. Daerah pertanian yang subur, banyak puspa ragam tanaman, baik yang dibudi daya maupun yang tumbuh secara alamiah. Hijau menyapa dalam keasrian alam yang padu menjadi bentangan keindahan yang tiada duanya. Subhanallah
Desaku, dan mungkin juga desa Anda semua, karena satu kesatuan wilayah Indonesia, sesungguhnya hanya memiliki dua musim saja. Di dalam rentang waktu satu tahun, karena pengaruh bentuk iklim, terkait pula dengan letak astronomis dan letak geografis, desa-desa di seluruh Indonesia hanya punya musim panas/kemarau dan musim hujan. Berbeda dengan beberapa negara lain di dunia yang memiliki hingga 4 jenis musim.
Meski demikian, desaku dan juga desa Anda, tak pernah mau terjebak dalam dua jenis musim. Satu tahun adalah waktu yang panjang untuk sekadar dinikmati dalam nuansa hujan dan panas semata. Tidak dalam hasrat mengalahkan jumlah musim di negara lain, desa-desa di Indonesia juga memiliki jumlah musim yang sangat banyak. Sebanyak jenis tanaman. Ada musim tanam, ada musim panen. Sebanyak jenis buah-buahan. Ada musim durian, musim duku, musim cempedak, musim rambutan, musim mangga, dan silakan Anda perpanjang sendiri daftarnya. Pastinya, ada banyak musim.
Ada satu hal terindah yang begitu rapi terlipat di laci ingatanku. Aku bahkan tak pernah berniat mengabadikannya, namun ia mendekam begitu dalam di sana. Saat gerimis, memori itu kerap meloncat ke permukaan pikiran. Dan memaksaku kembali ke masa lalu.
“Musim kopi” adalah kenangan terindah di ingatanku itu. Kenangan dari masa kecil yang enggan terkubur dalam lupa. Aku ingat, musim kopi selalu diawali dari gerimis, lalu menjadi hujan yang intens. Daun-daun bunga kopi hijau terang dalam basah. Terlihat segar penuh gairah usai dicumbu hujan.
Di salah satu pagi, saat mata belum sepenuhnya terbuka, hidungku lebih dahulu mengabarkan berkah itu. Aroma bunga kopi di antara gerimis pagi hari, semerbak yang tak cukup digambarkan dengan kata wangi, ah, itu sedap bukan kepalang.
Ketika itu, budi daya kopi menjadi tulang punggung penghidupan kami. Saat aku turun dari dipan tanpa kasur dan berjalan ke luar rumah. Meski gerimis, emak dan bapak telah berkeliling di pekarangan rumah yang penuh dengan tanaman kopi. Mereka menyibak daun-daun kopi yang basah, sembari mengagumi putihnya bunga kopi.
Bunga kopi yang baru mekar, memekarkan pula bunga harapan di hati. Harapan kepada berkah Allah, dan doa-doa yang diselipkan. Agar kiranya bunga kopi ini menjadi buah kopi semua. Lebat, padat, dan besar butirannya.
Kami menjaganya sepenuh hati. Sembari menyiangi rerumputan pengganggu tanaman kopi, bersabar mengikuti proses perubahan dari bunga menjadi butiran kecil rumpun biji kopi. Semakin besar buah kopi itu, semakin besar pula harapan kami, hingga ia menguning, lalu matang memerah.
Tibalah saat panen. Keluargaku tak memperkerjakan orang lain untuk memetik buah kopi. Aku dan kakak-kakakku dengan semangat membantu memetik buah kopi yang telah matang. Berunang (keranjang khas daerah Bengkulu yang terbuat dari rotan, red) menggayut di punggung dengan tali melilit di kening. Ketika itu, kami seperti tengah berpesta dan berlomba memetik kopi, di antara senda gurau dan hardikan bapak yang melihat kemungkinan polah kami dapat merusak batang kopi.
Aku tak perlu jelaskan bagaimana proses pasca panen selanjutnya. Kopi itu sebagian kami jual dan sebagian kecil kami nikmati. Kami jual untuk memutar roda kehidupan dan lebih banyak untuk biaya pendidikan.
Mungkin inilah yang membuat kenangan musim kopi begitu lekat terpatri di dalam bilik ingatan. Dari awal proses hingga akhir, dan hasilnya, selalu menumbuhkan harapan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Indah pula untuk dinikmati. Sampai hari ini aku masih menjadi penggemar Kopi Sumatera, rasa yang aku kenali dari masa anak-anak. Sering di antara sesapan saat menikmati kopi, kenangan tentang musim kopi nongol kembali.
Pagi ini, 11 Juli 2023, kopi terasa hambar buatku. Di kotaku dan juga di kota Anda, saat ini sedang dilanda musim yang lain. Musim politik. Hidungku tak mampu menghirup wanginya harapan. Tak ada kelopak putih kembang politik yang indah semerbak wangi, layaknya bunga kopi.
Aku hanya mencium aroma busuk korupsi dan kolusi yang entah untuk tujuan apa; dan para politisi saling berlomba membuka kuburan-kuburan aib itu. Aku cuma membaca caci maki. Hanya mendengar fitnah, intrik, dan saling menelanjangi kebusukan.
Menjanjikan Indonesia yang lebih baik, bagaimana mungkin terjadi, jika masih oligarki kemarin yang menabuh orkestra? Bagaimana mungkin kami percaya janji keadilan sosial, jika kronisme begitu telanjang dipertontonkan?
Saat musim durian tiba, aku telah dapat nikmat dari aromanya sebelum buahnya aku cicipi. Saat musim rambutan tiba, mataku bahkan telah penuh gairah dan harapan melihat gerumbulan buah rambutan yang kuning memerah di dahannya. Namun saat musim politik ini tiba, nikmat apa yang aku dapatkan? Justru begitu banyak polusi yang aku dengar dan lihat. Tidak menumbuhkan harapan tentang Indonesia yang lebih baik, malah dinamikanya kerap mengeruhkan batin dan pikiran setiap kali aku membaca berita politik!
Sebuah ladang yang tak memberi banyak ruang pada harapan. Mungkinkah suatu hari nanti musim politik akan semenggairahkan musim kopi? Entahlah.

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!