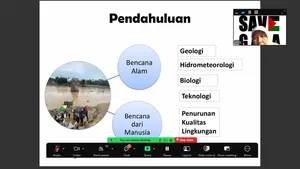“Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman” – QS. At-Taubah: 128
Berpolitik yang benar itu seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah selesai dalam hidupnya. Artinya, ia telah mampu mengatasi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Setelah itu, baru kemudian memikirkan nasib orang lain.
Itulah makna politik yang benar. Berpolitik itu sebagai bentuk pengabdian bagi orang yang cukup, mampu, dan mau berbuat baik untuk orang banyak.
Apa yang dilakukan Nabi Nuh AS dan para Nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW, itulah model berpolitik yang benar. Alih-alih bertanya apa yang mereka dapatkan, mereka justru mengalami penderitaan, pengorbanan, tetapi tetap memberi kasih sayang, dengan harapan umat tidak berada dalam penderitaan yang panjang (dalam kebodohan dan kemiskinan).
Orang berkecukupan, punya kemampuan dan kemauan untuk berbuat baik kepada orang lain, umumnya dikenal sebagai elit politik. Sudah sewajarnya mereka membantu pihak yang kekurangan atau dikenal dengan istilah kawulo alit.
Berkecukupan di dalam konteks ini adalah aspek ilmu, kearifan atau kematangan hidup, juga cukup dalam menghadapi hidup, baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kecukupan yang lain. Sedangkan kekurangan dalam hal ini terkait pula dengan aspek ilmu, pengalaman, kemandirian ekonomi, tentang hidup dan kehidupan (powerless). Karenanya, posisinya disebut orang yang dikuasai. Di Jawa dikenal dengan kawulo alit.
Baca juga: Bahasa Rakyat Adalah “Bahasa Beras”
Politik Bermakna tidak Tergantung Sistem Politiknya
Berpolitik yang bermakna itu bisa lahir dalam sistem politik apa pun. Ada banyak contoh raja yang baik atau sebaliknya. Juga ada Presiden yang baik atau selanjutnya.
Jadi, orang cukup atau elit politik bisa saja raja, seperti Raja Sulaiman AS, Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei), Ratu Inggris dan lain-lain, atau bisa Presiden seperti Erdogan (Turki) dan lain-lain. Orang cukup dan baik bisa di mana-mana dan dalam bentuk pemerintahan apa pun. Bagi orang cukup dan baik, tidak perlu ada alasan untuk berbuat kebaikan. Baik untuk dirinya dan umat serta bangsanya.
Di dalam ilmu politik, setiap sistem politik selalu ada kelebihan dan kekurangan, tergantung siapa yang berkuasa (mampu dan mau berbuat baik). Maka, banyak pemimpin yang cukup dan baik (elit politik) tidak tergantung pada sistem pemerintahannya, sebagaimana dicontohkan di beberapa negara di atas.
Plus Minus Sistem Demokrasi dan Kasus Indonesia
Demokrasi di Yunani Kuno berjalan selama ribuan tahun, hingga abad ke-6 SM. Athena, contohnya, memulai demokrasi dengan Cleosthenes sebagai tokoh utamanya. Filosofinya, pemilik kekuasaan dan pengambil kebijakan adalah rakyat. Dari, oleh, dan untuk rakyat.
Di dalam konteks demokrasi, kondisi antara elit politik (penguasa) dan yang dikuasai sifatnya setara, sama-sama mampu (dari segi keilmuan atau terdidik dan secara ekonomi). Makanya, hubungannya bersifat transaksional dan diperbarui kontraknya dalam pemilu.
Idealnya, sistem demokrasi memiliki mekanisme check and balance. Ada kelompok penguasa dan kelompok oposisi yang sama-sama terhormat. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Hubungan dan kondisi antara elit politik dan kawulo alit akan membentuk sistem politik suatu negara. Bisa jadi, kondisi elit politik yang mampu dan baik dan di sisi lain masyarakat yang miskin dan bodoh itu menggunakan sistem kerajaan. Di situ kedudukan penguasa bagai orang tua yang mampu dan baik. Juga berperan sebagai guru dan pengayom. Inilah sistem politik yang pernah dicita-citakan oleh Socrates dan Al Farobi.
Baca juga: Dua Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal
Di dalam tataran empiris, banyak raja yang membawa kemakmuran bagi bangsanya. Misalnya, Raja Daud AS, Raja Sulaiman AS, Sultan Hassanal Bolkiah, Ratu Inggris, dan lain-lain. Di sisi lain, banyak Presiden (dalam sistem demokrasi) yang justru membawa bangsa dan negaranya dalam kebangkrutan dan penderitaan serta kemiskinan.
Namun, demokrasi akan benar-benar menjadi musibah jika tidak ada lagi check and balance. Ada legislatif dan yudikatif, tetapi dalam kendali eksekutif. Tidak ada oposisi. Masyarakat dalam kondisi powerless (tidak berdaya) karena dalam kemiskinan dan kebodohan. Di dalam kondisi seperti itu, maka sistem demokrasi mudah dikendalikan oleh segelintir orang (oligarki) yang mengendalikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada orang yang menyebutnya sebagai negara kerajaan yang seolah-olah demokrasi. Substansinya kerajaan, tetapi berwajah demokrasi.
Di dalam kasus Indonesia ada sekitar 70% mereka yang berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Mereka memilih pemimpin bukan karena figurnya (apakah cukup dan baik), juga bukan karena programnya (bisa memperbaiki kehidupan rakyatnya), tetapi apa yang dilihat dan diterima hari ini. Uang dalam amplop, sembako, dan lain-lain. Harganya tidak seimbang dengan penderitaan yang mereka akan rasakan tidak hanya 5 tahunan, tetapi sepanjang hidup. Karena bagi mereka, pemilu dan tidak ada pemilu tidak berpengaruh dalam kehidupannya, tetap dalam kemiskinan dan kebodohan.
Kesimpulan
Sistem demokrasi di Indonesia belum memenuhi syarat sebagaimana yang dibayangkan oleh Cleosthenes (Yunani), yaitu rakyat yang berdaya. Punya posisi bargaining yang sama dengan elit politik. Sehingga mudah dimanipulasi dan diperdayai oleh elit politik yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri dan keluarganya, yaitu oligarki.

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili
Bangun Indonesia dengan Literasi!